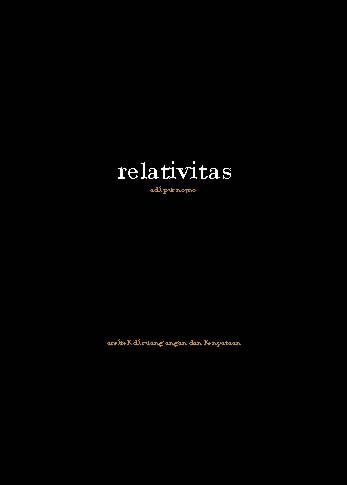Seperti apakah buku yang dikategorikan sebagai buku arsitektur? Baru-baru ini saya membeli buku rilisan IAI berjudul “
Long Road Towards Recognition”, dengan harga yang (ehm) lumayan juga. Terus terang saya sedikit kecewa ketika tahu bahwa ternyata buku tersebut adalah
yet another “coffee-table” books, seperti standar buku-buku arsitektur yang rilis sebelumnya. Ambil contoh dari awalmula buku “
coffee-table” masuk dalam rilisan penerbit luar yang menampilkan eklektisisme arsitektur daerah di Indonesia (yang menstandarkan imej arsitektur Indonesia sebagai arsitektur “etnik”). Kemudian muncul rilisan IAI dalam bentuk “
Karya-Karya Arsitek Indonesia” (
pardon me, kalo ternyata judulnya sedikit kurang tepat),
yet another coffee-table-book. Juga “
Indonesian Architecture Now”, dari Imelda Akmal, menyusul buku kuning-nya AMI (
Karya-Karya Arsitek Muda Indonesia: The Next Gen), dan puluhan buku lain yang rilis kemudian.
Saya ingat suatu kali
wonder and amazed sama sebuah buku ramping (dari sisi dimensi buku) berjudul “
AMI: Perjalanan 1999” yang dipinjam dari seorang teman kuliah.
At last -dalam hati saya- ada juga yang berpikir untuk membagi pengalaman arsitekturalnya tanpa terjebak profanitas media visualisasi. Foto, denah, dan berbagai tampilan “matang” visual dari objek arsitektur memang penting (sekaligus menarik); tetapi sebagai bahan referensi yang muncul dalam bentuk buku (media literer), niscaya penjelasan proses “berarsitektur” ke arah sana jauh lebih penting. Buku "AMI: Perjalanan 1999" sedikit banyak menjelaskan tentang realita dan proses berpikir ke-arsitektur-an yang relatif berbeda dari kita membuka halaman
coffee-table-books. Para pelaku ziarah arsitektur tersebut menuturkan pengalaman meruang mereka dalam objek-objek arsitektur dunia; memberikan suatu cara pandang baru bagi saya untuk lebih menelaah arsitektur tidak hanya sekedar bungkus imej luaran dari foto-foto yang kilau. Arsitektur lebih kepada studi tentang ruang dalam yang simple sekaligus kompleks (karena harus dirasakan), begitulah yang saya rasakan dalam membaca buku "AMI: Perjalanan 1999" di tahun-tahun awal kuliah.
Medio masa studi kuliah saya, ada referensi kuat untuk “mencoba” membuka sebuah buku sakit (menurut Rafael Arsono, sahabat yang pertama kali meminjamkan buku "AMI:Perjalanan 1999"). Sedikit
flashback, awal kuliah saya juga mendapat referensi dari lembaran
slide kuliah tentang arsitek bernama Rem Koolhaas. Waktu itu Koolhaas jarang dilirik, karena seolah semua mahasiswa tengah terbius dengan kemegahan bangunan Frank Gehry atau kompleksitas Peter Eisenman. Beberapa tahun kemudian, saya berkesempatan untuk membeli buku seharga satu juta rupiah (!), karangan Koolhaas yang rasanya cukup untuk menindih lalat sampai gepeng karena kemasifan-nya. Judul buku tersebut adalah “
S,M,L,XL” yang dikerjakannya bersama seniman grafis: Bruce Mau. Buku tersebut merupakan skala introspektif dari seorang arsitek Belanda yang bisa dibilang “gila” dalam menuturkan buah pikirnya. Pada dasarnya, "S,M,L,XL" merupakan kumpulan karya Koolhaas yang diklasifikasi berdasarkan besaran atau volume-nya. Tetapi agar tidak menjadi objek “pemerkosaan visual” ala
coffee-table-books, Koolhaas mengagendakan Bruce Mau untuk sedikit merusak visual dari grafik buku tersebut. Disamping itu, juga terdapat banyak sekali manifesto pikir dari seorang Rem Koolhaas yang tertuang mejadi seperti
diary perancangan. Buku tersebut sedemikian “sakit” sehingga mampu menularkan virus hebat bagi saya berupa pandangan bahwa arsitektur, saat ini, adalah komoditas dari produk budaya instan bernama
fashion (
hence, klasifikasinya berdasarkan ukuran seperti halnya produk massal garmen).

Dari "S,M,L,XL" tersebut saya mulai berpikir tentang buku arsitektur yang baik. Proses pembentukan pola pikir untuk menjadikan sebuah objek arsitektur adalah suatu hal yang harus diagendakan untuk dibagi kepada publik, dibandingkan menyajikan dalam bentuk jadi (seperti halnya “album foto”), atau terlalu mentah (teoritis). Buku arsitektur sebagai media referensi tentang objek aristektur, atau arsiteknya sendiri harus bisa menjelaskan runutan cara berpikir dari arsitek yang bersangkutan untuk menghasilkan karya-karyanya. Buku "AMI: Perjalanan 1999" menginformasikan praduga-praduga yang berpangkal dari apresiasi rombongan arsitek Indonesia di dalam karya-karya arsitek dunia. Hal itu juga positif membangun kesadaran berpikir proses, (misalnya) bahwa keunikan
alley yang terdapat di Kunsthal pasti melalui serangkaian proses penggabungan sirkulasi urban dengan sirkulasi galeri (setidaknya menurut pendapat apresiator-nya). Bahwa kemegahan bangunan Gehry di Bilbao baru sangat terasa setelah mereka merasakan sendiri keterkaitan kehadiran massa skulpturalis itu dalam konteks ruang kota Bilbao. Juga bahwa kenapa kota Lille menjadi sebuah laboratorium unik dari definisi kota “Uni-Eropa” bisa kita rekam dari penuturan Koolhaas via buku "S,M,L,XL". Hal-hal demikian akan kembali me-
reshape sekaligus sebagai media diskusi yang menarik bagi pembacanya, daripada sekedar mengagumi hasil karya arsitektur melalui foto-foto “matang”-nya. Pengaruh positifnya, tentunya sebagai apresiator, kita akan turut tertantang untuk mencoba menggabungkan pengalaman proses desain ke dalam rancangan. Sementara, buku-buku teoritis akan dicap sebagai buku langitan karena
untouchable (seperti halnya “
Complexity and Contradiction”-nya Venturi yang menurut saya sampe saat ini masih berupa wacana).
Quit pro quo, buku
coffee-table juga akan dicap sebagai buku yang menyemikan plagiat (atau inspirasi). Mungkin dari sini kita bisa menarik suatu kesimpulan kenapa muncul “gaya arsitektur” yang lantas menjadi alibi bagi duplikasi arsitektur.
Dari eksposisi pribadi tersebut, lantas saya ngambil kesimpulan jika di Indonesia masih sangat kekurangan buku arsitektur yang saya kategorikan sebagai buku “baik”. Buku-buku kompilasi karya yang muncul belakangan ini tengah mendominasi khasanah literatur arsitektur di Indonesia. Dari karya-karya Imelda Akmal, dengan segala hormat terhadap usaha kompilasinya, sampai ke rilisan IAI. Kita membutuhkan buku-buku
sharing pengalaman (terutama ruang) dan “bercerita” seperti halnya "AMI: Perjalanan 1999" sebagai media pendidikan dan sumber referensi yang lebih membangun terhadap alih-generasi arsitektur Indonesia, secara khusus dan publik pada umumnya. Mungkin dengan munculnya buku yang lebih “bercerita” tersebut dunia arsitektur akan turut menyumbangkan visinya merubah budaya instan bangsa Indonesia menjadi budaya proses.
End NoteAkhir 2004 lalu, Yori Antar merilis bukunya berjudul “
East Meet West”. Buku yang bercerita tentang salah satu karya desain Yori, meski dalam format
coffee-table (dominasi unsur visual yang profan), tetapi dengan fokus terhadap satu buah objek dan ditulis notabene oleh desainernya sendiri, membuat buku ini menjadi sumber referensi berharga tentang proses arsitektural. Berbeda dengan buku kompilasi yang terlihat “kurang menggigit” dalam hal apresiasinya meski dilengkapi dengan narasumber primer dari arsitek-nya, tetapi yang muncul rata-rata masih merupakan “komentar” instan terhadap visual (tak jauh beda dengan edisi khusus
annual majalah ASRI, bertajuk "
Skala+").
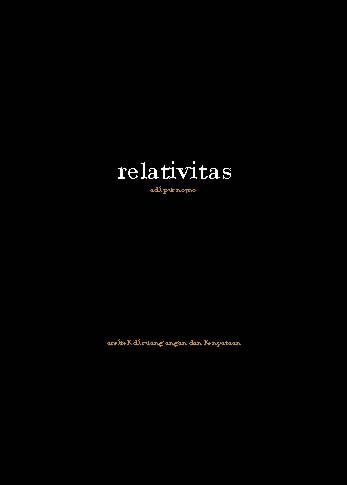
Kemudian di akhir 2005, Adi Purnomo mengeluarkan buku berjudul “
Relativitas – Arsitek di Ruang Angan dan Kenyataan”. Buku setebal 250-an halaman yang berformat BW tersebut menjadi “curhat”-an dari arsitek asal Jogjakarta tersebut. Di sini saya merekomendasikan buku tersebut kepada segenap pemerhati arsitektur sekalian. Terutama generasi muda arsitektur Indonesia (mahasiswa, terutama) untuk ikut menyelami proses berpikir Adi Purnomo dalam menghasilkan desain, yang membenturkan antara idealisme dan realisme. Satu lagi pemikiran tentang proses. Juga kepada arsitek “mapan” di Indonesia,
I urge you to release such a book!
Bolehlah kita beroptimis mengenai dunia literatur arsitektur di Indonesia di masa depan untuk menjadi lebih baik berdasarkan dua preseden tokoh arsitektur Indonesia tersebut dan karya literatur-nya. Serta (berharap) membantu mengubah perspektif budaya bangsa kita dari budaya instan menjadi budaya proses.
Never be too late to change.
 Title: The State of Architecture at the Beginning of the 21st Century
Title: The State of Architecture at the Beginning of the 21st Century