Saya ingat suatu kali wonder and amazed sama sebuah buku ramping (dari sisi dimensi buku) berjudul “AMI: Perjalanan 1999” yang dipinjam dari seorang teman kuliah. At last -dalam hati saya- ada juga yang berpikir untuk membagi pengalaman arsitekturalnya tanpa terjebak profanitas media visualisasi. Foto, denah, dan berbagai tampilan “matang” visual dari objek arsitektur memang penting (sekaligus menarik); tetapi sebagai bahan referensi yang muncul dalam bentuk buku (media literer), niscaya penjelasan proses “berarsitektur” ke arah sana jauh lebih penting. Buku "AMI: Perjalanan 1999" sedikit banyak menjelaskan tentang realita dan proses berpikir ke-arsitektur-an yang relatif berbeda dari kita membuka halaman coffee-table-books. Para pelaku ziarah arsitektur tersebut menuturkan pengalaman meruang mereka dalam objek-objek arsitektur dunia; memberikan suatu cara pandang baru bagi saya untuk lebih menelaah arsitektur tidak hanya sekedar bungkus imej luaran dari foto-foto yang kilau. Arsitektur lebih kepada studi tentang ruang dalam yang simple sekaligus kompleks (karena harus dirasakan), begitulah yang saya rasakan dalam membaca buku "AMI: Perjalanan 1999" di tahun-tahun awal kuliah.
Medio masa studi kuliah saya, ada referensi kuat untuk “mencoba” membuka sebuah buku sakit (menurut Rafael Arsono, sahabat yang pertama kali meminjamkan buku "AMI:Perjalanan 1999"). Sedikit flashback, awal kuliah saya juga mendapat referensi dari lembaran slide kuliah tentang arsitek bernama Rem Koolhaas. Waktu itu Koolhaas jarang dilirik, karena seolah semua mahasiswa tengah terbius dengan kemegahan bangunan Frank Gehry atau kompleksitas Peter Eisenman. Beberapa tahun kemudian, saya berkesempatan untuk membeli buku seharga satu juta rupiah (!), karangan Koolhaas yang rasanya cukup untuk menindih lalat sampai gepeng karena kemasifan-nya. Judul buku tersebut adalah “S,M,L,XL” yang dikerjakannya bersama seniman grafis: Bruce Mau. Buku tersebut merupakan skala introspektif dari seorang arsitek Belanda yang bisa dibilang “gila” dalam menuturkan buah pikirnya. Pada dasarnya, "S,M,L,XL" merupakan kumpulan karya Koolhaas yang diklasifikasi berdasarkan besaran atau volume-nya. Tetapi agar tidak menjadi objek “pemerkosaan visual” ala coffee-table-books, Koolhaas mengagendakan Bruce Mau untuk sedikit merusak visual dari grafik buku tersebut. Disamping itu, juga terdapat banyak sekali manifesto pikir dari seorang Rem Koolhaas yang tertuang mejadi seperti diary perancangan. Buku tersebut sedemikian “sakit” sehingga mampu menularkan virus hebat bagi saya berupa pandangan bahwa arsitektur, saat ini, adalah komoditas dari produk budaya instan bernama fashion (hence, klasifikasinya berdasarkan ukuran seperti halnya produk massal garmen).

Dari "S,M,L,XL" tersebut saya mulai berpikir tentang buku arsitektur yang baik. Proses pembentukan pola pikir untuk menjadikan sebuah objek arsitektur adalah suatu hal yang harus diagendakan untuk dibagi kepada publik, dibandingkan menyajikan dalam bentuk jadi (seperti halnya “album foto”), atau terlalu mentah (teoritis). Buku arsitektur sebagai media referensi tentang objek aristektur, atau arsiteknya sendiri harus bisa menjelaskan runutan cara berpikir dari arsitek yang bersangkutan untuk menghasilkan karya-karyanya. Buku "AMI: Perjalanan 1999" menginformasikan praduga-praduga yang berpangkal dari apresiasi rombongan arsitek Indonesia di dalam karya-karya arsitek dunia. Hal itu juga positif membangun kesadaran berpikir proses, (misalnya) bahwa keunikan alley yang terdapat di Kunsthal pasti melalui serangkaian proses penggabungan sirkulasi urban dengan sirkulasi galeri (setidaknya menurut pendapat apresiator-nya). Bahwa kemegahan bangunan Gehry di Bilbao baru sangat terasa setelah mereka merasakan sendiri keterkaitan kehadiran massa skulpturalis itu dalam konteks ruang kota Bilbao. Juga bahwa kenapa kota Lille menjadi sebuah laboratorium unik dari definisi kota “Uni-Eropa” bisa kita rekam dari penuturan Koolhaas via buku "S,M,L,XL". Hal-hal demikian akan kembali me-reshape sekaligus sebagai media diskusi yang menarik bagi pembacanya, daripada sekedar mengagumi hasil karya arsitektur melalui foto-foto “matang”-nya. Pengaruh positifnya, tentunya sebagai apresiator, kita akan turut tertantang untuk mencoba menggabungkan pengalaman proses desain ke dalam rancangan. Sementara, buku-buku teoritis akan dicap sebagai buku langitan karena untouchable (seperti halnya “Complexity and Contradiction”-nya Venturi yang menurut saya sampe saat ini masih berupa wacana). Quit pro quo, buku coffee-table juga akan dicap sebagai buku yang menyemikan plagiat (atau inspirasi). Mungkin dari sini kita bisa menarik suatu kesimpulan kenapa muncul “gaya arsitektur” yang lantas menjadi alibi bagi duplikasi arsitektur.
Dari eksposisi pribadi tersebut, lantas saya ngambil kesimpulan jika di Indonesia masih sangat kekurangan buku arsitektur yang saya kategorikan sebagai buku “baik”. Buku-buku kompilasi karya yang muncul belakangan ini tengah mendominasi khasanah literatur arsitektur di Indonesia. Dari karya-karya Imelda Akmal, dengan segala hormat terhadap usaha kompilasinya, sampai ke rilisan IAI. Kita membutuhkan buku-buku sharing pengalaman (terutama ruang) dan “bercerita” seperti halnya "AMI: Perjalanan 1999" sebagai media pendidikan dan sumber referensi yang lebih membangun terhadap alih-generasi arsitektur Indonesia, secara khusus dan publik pada umumnya. Mungkin dengan munculnya buku yang lebih “bercerita” tersebut dunia arsitektur akan turut menyumbangkan visinya merubah budaya instan bangsa Indonesia menjadi budaya proses.
End Note
Akhir 2004 lalu, Yori Antar merilis bukunya berjudul “East Meet West”. Buku yang bercerita tentang salah satu karya desain Yori, meski dalam format coffee-table (dominasi unsur visual yang profan), tetapi dengan fokus terhadap satu buah objek dan ditulis notabene oleh desainernya sendiri, membuat buku ini menjadi sumber referensi berharga tentang proses arsitektural. Berbeda dengan buku kompilasi yang terlihat “kurang menggigit” dalam hal apresiasinya meski dilengkapi dengan narasumber primer dari arsitek-nya, tetapi yang muncul rata-rata masih merupakan “komentar” instan terhadap visual (tak jauh beda dengan edisi khusus annual majalah ASRI, bertajuk "Skala+").
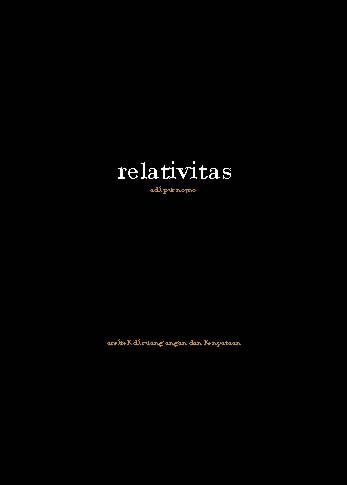
Kemudian di akhir 2005, Adi Purnomo mengeluarkan buku berjudul “Relativitas – Arsitek di Ruang Angan dan Kenyataan”. Buku setebal 250-an halaman yang berformat BW tersebut menjadi “curhat”-an dari arsitek asal Jogjakarta tersebut. Di sini saya merekomendasikan buku tersebut kepada segenap pemerhati arsitektur sekalian. Terutama generasi muda arsitektur Indonesia (mahasiswa, terutama) untuk ikut menyelami proses berpikir Adi Purnomo dalam menghasilkan desain, yang membenturkan antara idealisme dan realisme. Satu lagi pemikiran tentang proses. Juga kepada arsitek “mapan” di Indonesia, I urge you to release such a book!
Bolehlah kita beroptimis mengenai dunia literatur arsitektur di Indonesia di masa depan untuk menjadi lebih baik berdasarkan dua preseden tokoh arsitektur Indonesia tersebut dan karya literatur-nya. Serta (berharap) membantu mengubah perspektif budaya bangsa kita dari budaya instan menjadi budaya proses. Never be too late to change.

7 comments:
Prolog...
Kajian tentang arsitektur pada dasarnya tidak boleh lepas dari kajian-kajian seni dan sosial. Sewaktu saya kuliah, mahasiswa-mahasiswa 'frustasi' yang dengan sengaja atau tidak sengaja menghujat arsitektur dari hati yang paling dalam dengan sebutan "art shit texture" bahkan lebih manusiawi lagi "asu tektur", yang pada dasarnya menunjukkan identitas diri arsitektur yang tidak berbentuk dan hina. Arsitektur sebagai seni paling rendah dari semua cabang seni. Sedangkan mahasiswa lain yang lebih mapan dan menikmati 'kemewahan' arsitektur dengan bangga menunjukkan dadanya: wis arsitek tur ugm, sudah arsitek, ugm lagi.
Buku untuk Tidak Dibaca...
Ada beberapa ujaran menyindir tentang mahasiswa arsitektur: "...kalian ini jauh-jauh disekolahkan di Jogja seharusnya buat belajar, malah nggambar...". Arsitek itu pemikir atau tukang gambar? Ada lagi dosen saya, Adi Utomo Hatmoko yang pernah berujar: "...nek nggambar ra mikir, nek mikir ra nggambar..." Arsitek itu bukan seniman lukis, jadi harus berfikir. Tapi arsitek itu bukan filsuf, jadi harus ada karya nyatanya. Begitulah kira-kira...
Berawal dari kenyataan semasa kuliah, buku-buku arsitektur itu se'eksklusif' artis ibukota. Mahal dan tak terjangkau. Kalaupun terjangkau, itu pastilah artis dangdut--tahulah artis dangdut! Pun, semua buku itu impor dengan kertas yang bagus-bagus dan gambar yang menawan. Jadilah buku-buku arsitektur sebagai bukan buku pelajaran, tapi komik untuk dilihat gambarnya. Berbicara kedalaman isi, tidak penting rasanya. Saya dan kawan-kawan kenal Tadao Ando, Richard Meir, Aldo Rosi, FLW, dll ya dari melihat gambar. Dengan melihat gambar dan sedikit narasi saja kita tahu style dan keinginan mereka seperti apa. Coba bandingkan dengan buku-buku arsitektur terbitan lokal, Karya Arsitek Indonesia, atau karya-karya arsitek AMI. Gaya penuturannya yang lebih men'dokter'kan arsiteknya membuat saya muak. Belum lagi buku Imelda Akmal 'Indonesia Architecture Now', bullshit! Kenapa sudut pandang arsitektur menjadi semakin sempit ketika dijadikan buku. Sudah gitu diembel-embeli Indonesian Architecture...now! Apakah arsitektur Indonesia kini itu yang stylenya keunpar-unparan, atau yang keami-amian. Saya tidak melihat sinergi karya arsitektur Indonesia yang sesungguhnya. Sudahlah, kita memang tidak bisa terus-menerus mengatakan arsitektur vernakular yang ber-genius loci adalah karya arsitektur Indonesia, Indonesia banget. Tapi juga karya arsitektur Indonesia tidak sesempit itu. Lalu apa bedanya buku itu dengan majalah Asri, Indonesia Design, dan tabloid-tabloid pinggir jalan. Jangan-jangan buku itu kliping dari majalah dan tabloid. Uhh, buku itu harus penting dan bermakna baik.
End of story...
Sejujurnya saya takut membeli buku-buku arsitektur keluaran lokal. Takut kecewa... Harganya memang tidak semahal buku impor, tapi sekali lagi saya takut kecewa. Sama seperti saya takut nonton di bioskop dengan film Indonesia yang diputar. Ceritanya mungkin bagus, tapi gara-gara artisnya yang tidak berbakat jadi pemain film, jadilah kecewa datang. Sama juga ketika terpaksa nonton sinetron, kalau tidak kecewa, ya jadi gila...masak kerjaan artis-artis sinetron itu ngomong sendiri--atau mereka memang gila.
Rilisan Adi Purnomo bisa dipertimbangkan bos. Apalagi itu kakak-angkatan elo sendiri (hehe). Gw merasa banyak berdialog sama dia (via buku) mengenai keresahan-keresahan akibat terlalu sistematis-nya dunia arsitektur di Indonesia. Atau mungkin gw suka karena relatif kesamaan berpikir-nya aja yah? Tapi coba dulu, buku itu beda.
Harus diakui memang bahwa tidak banyak buku-buku terbitan lokal karya anak negeri—dalam hal ini yang memiliki latar belakang pendidikan/ profesi dari arsitektur atau desain interior—yang gampang ditemui di pasar. Mungkin itu yang jadi salah satu kendala kenapa akhirnya saat ada buku baru di dunia arsitektur launching, banyak kritikan, komentar dan hujatan mengenai ke’layakan’ isinya.
Gw sendiri termasuk salah seorang yang mengamini pernyataan bahwa mutu buku-buku literatur keluaran lokal masih jauuuhh...bgt dari kata sempurna—dari segi isi maupun layout yg ’engga banget’—dibanding dengan buku-buku impor (yang harganya mahal bgt n bisa menghabiskan uang saku berbulan-bulan kalau niat bgt pgn beli!).
toh meski begitu, kita g bisa menutup mata juga kalau ada segelintir orang atau kelompok yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat awam dan praktisi arsitektur yang haus akan informasi-informasi yang terjadi dalam khasanah arsitektur di Indonesia.
Gw cukup salut dengan mereka-mereka itu karena setidaknya mereka punya nyali untuk membagi sedikit dari pengetahuan yang mereka punya itu, berani buat rugi dan dihujat kalo isinya cupu(iya donk.....orang yang nerbitin ’buku arsitektur’ itu kan niat awalnya pasti karena mereka ingin share something yang mereka pikir bisa menambah wawasan orang lain, selain memperkaya khasanah perbukuan arsitektur juga. Soal laku tidaknya, apalagi bisa jadi best seller pasti bukan tujuan utama).
Gw termasuk orang yang lebih suka baca buku yang cara ulasannya ’bertutur’, bercerita secara deskriptif. Gw merasa lebih bisa ’masuk’ dan mengerti, bisa membayangkan juga seolah-olah gw ada di dalam ’proses’ cerita itu.
Tibet di Otak—hasil karya keroyokannya Yori Antar, Jay Subiakto, Enrico Soekarno, Raudia Kepper, Ella Baudia sampe Krish Suharnoko so far jadi the best architecture favorit book terbitan lokal gw (gw baru aja selesai baca buku ini sampe tamat kmrn di kantor dan gw bnr2 amazed bgt ma cara bertutur mereka semua. Perbedaan gaya bertutur mereka justru membuat buku ini semakin ’hidup’ dan menggigit! Bikin gw mupeng bgt having such kind experience). Memang isinya lebih ke kisah perjalanan Yori dkk sewaktu mengunjungi negeri Tibet, tapi toh buku itu layak masuk jajaran buku arsitektur karena cara bertutur mereka tidak lepas dari kacamata arsitektur juga (bukankah arsitektur itu ilmu yang luas sekali, meliputi kehidupan sosial budaya setempat dan kaya akan pengalaman ruang?).
Relativitas karya Mamo (Adi Purnomo) juga mungkin bisa jadi my next fave book. g bisa kasih komentar ttg buku ini karena sejauh ini gw baru sebatas buka-buka beberapa halaman aja, belum sampe khatam bacanya meskipun di kantor buku ini buanyaaakk banget! (kantor gw jualan buku soalnya;p) Beberapa temen gw highly recommended buku ini (termasuk ulasan ttg buku ini di blog elo, mimz..he2).
Tentang mengapa buku-buku arsitektur lokal yang cenderung lebih menganut gaya ’coffe table’ book, mungkin sebagian besar disebabkan karena budaya masyarakat kita yang masih lebih menyenangi hal-hal yang dari luar nampak bagus, megah, indah, mewah. Masyarakat kita masih senang untuk memoles tampak luarnya saja. Dan gw pikir, pendekatan yang harus dipakai kalau benar-benar ingin ’menjangkau’ mereka ya dengan memakai pola pikir demikian. Maka jadilah hasilnya buku-buku yang hanya sebatas ’galeri foto’ tanpa disertai informasi menyeluruh mengenai karya, apalagi proses desain sang arsitek hingga bisa mencapai final design seperti itu.
Imelda Akmal termasuk salah satu orang yang punya nyali untuk berani mengeluarkan buku dengan tajuk ’berat’ macam Indonesian Architecture Now. Buku itu sendiri keluar melalui proses panjang yang melelahkan, jadwal launchingnya saja mundur hingga 5 tahun. Kenapa gw bilang dia berani banget? Gimana engga, dengan judul yang membawa nama ”Indonesian Architecture” ditambah embel2 NOW pula (just like Eftianto said ;p) ekspektasi orang saat melihat isinya pasti tinggi sekali. Euforia orang lebih kepada rasa ingin tahu yang besar tentang ”gimana sih gambaran arsitektur indonesia sekarang?”. belum lagi kalau orang ternyata kecewa dengan isinya—yang dianggap tidak sepenuhnya menggambarkan wajah arsitektur indonesia saat itu—dia adalah orang pertama yang akan dihujat habis-habisan. Penuh resiko sekali dan punya beban moral tersendiri kalau gw bilang. That’s gw berusaha se-fair mungkin melihat kekurangan itu dari sudut pandang yang berbeda.
Indonesian Architecture Now sendiri target marketnya tuh lebih untuk pembuktian ke dunia luar bahwa orang Indonesia sendiri mampu kok untuk membuat sebuah buku yang isinya kompilasi karya-karya pilihan yang dianggap representatif mewakili wajah arsitektur Indonesia. G lucu kan kalau ada buku dengan judul semacam itu tapi yang bikin orang bule?! Kekalahan yg besar bgt kalau sampe kejadian!! That’s why wujud IAN cenderung jadi coffe table book apalagi dengan teks Inggrisnya itu. Soal kelayakan karya-karya yang ada di dalam buku itu disebut sebagai wajah arsitektur Indonesia saat ini, pada mulanya gw juga sempat bertanya-tanya siapakah ’dewan juri’ di balik buku itu yang menentukan layak tidaknya sebuah karya masuk ke IAN? Ada kriteria2 khusus g sih? Setelah mengajukan pertanyaan kesana-sini, mendiskusikan dengan beberapa teman, bahkan bertanya langsung dengan penyusunnya, gw baru sadar bahwa proses yang terjadi di balik pembuatan sebuah buku itu berat dan rumit sekali. G segampang yang selama ini gw pikir. Apalagi ini adalah buku yang memiliki beban besar, banyak orang yang mencintai dunia arsitektur ikut menyumbang saran dan ide mereka. Berpuluh-puluh kali debat dan diskusi serta deadlock terjadi. IAN 1 memang masih jauh sekali dari sempurna, namun setidaknya itu sudah merupakan langkah besar dan berani. Kalau ada yang berkomentar IAN adalah perpanjangan tangan untuk makin mengkultuskan karya-karya arsitek yang tergabung di AMI, gw pikir itu dari sudut mana kita melihat aja sih. Kalaupun kebetulan arsitek yang karyanya masuk di IAN adalah orang2 AMI, apa itu salah? Setidaknya orang2 yang aktif di AMI itu membuktikan bahwa mereka g hanya omong besar saja ingin merubah wajah arsitektur Indonesia. Kontribusi nyata mereka kan ya dengan terus menelurkan karya, kalau kemudian karya itu ada yang dianggap ’baik’ dan ’berhasil’ dari segi desain dan konsep, masa iya kita menghujat? Bukannya lebih baik buktikan juga dengan menghasilkan sesuatu yang kita anggap dapat memperbaiki dunia arsitektur kita, memberikan sumbangsih kita? Semua tidak bisa terjadi secara instan kan? It takes time...dan akan lebih cepat untuk diwujudkan kalau setiap individu yang mengaku peduli pada dunia arsitektur itu bahu-membahu ketimbang saling menjatuhkan dan menjelekkan satu sama lain.
Semua orang punya peran dan bagiannya masing-masing. So far mereka-mereka yang berani nerbitin buku itu berusaha konsisten di jalur masing-masing. Yori dkk membagi pengalaman ruangnya dengan model buku seperti itu, Adi Purnomo menuangkan kegelisahannya dengan gayanya sendiri, sementara Imelda Akmal juga berusaha dengan segenap kemampuan yang dia bisa.
Kita semua boleh berharap agar IAN volume 2 dapat lebih baik lagi kualitas isinya nanti, tidak sekedar menjadi coffe table book semata tapi juga ada ’isi’nya, semoga...... Gw sendiri saat ini baru 1 bln bekerja di Architecture Writer Studio milik Imelda Akmal sebagai penulis junior. Tulisan ini gw buat bukan karena gw ingin membela kepentingan bos dan kantor gw semata. toh, gw masih termasuk orang baru di studio Imelda Akmal dan cara berpikir gw juga masih seperti orang luar yang banyak mencela kekurangan-kekurangan bukunya. Tapi setidaknya gw makin tahu bahwa mb’Imel benar-benar ingin memberikan edukasi yang benar pada masyarakat awam mengenai arsitektur dan interior. Dia sadar bahwa buku-bukunya akan menjadi alternatif referensi bacaan masyarakat sehingga dia benar-benar bertanggung jawab dengan isi bukunya agar tidak melakukan pembodohan pada masyarakat. Soal kekurangan2 yang masih ada itu, itu tugas kita yang peduli untuk terus memberikan komentar dan saran agar buku-buku itu tetap pada jalur yang benar—tidak sekedar mengejar oplah best seller, tidak melakukan edukasi yang salah pada masyarakat dan yang paling penting ada ’isi’nya.
Thanks Nov, udah ngasi pandangan...gw forward juga ke Anto ntar-nya (Eftianto).
Untuk kepentingan propaganda, buku-buku semacam "Indonesian Architecture Now" itu penting. Bagaimanapun, dengan muncul di semacam kompilasi internasional arsitek Indonesia lebih punya posisi tawar untuk mendapatkan proyek-proyek selanjutnya. Faktanya, IAI malah sering sekali melaunching buku semacam itu, dimana tentu aja gw curiga kalo itu sebetulnya media IAI untuk mempropagandakan arsitek lokal. Which was good, kalau dari kacamata profesional arsitek (terutama mereka yang nongol di proyek kompilasi). Tapi mari kita timbang resikonya. Dengan budaya bangsa kita yang sangat suka sekali mengkopi, kehadiran buku-buku semacam itu bisa saja "dipersalahkan" karena membawa stagnansi khasanah arsitektur Indonesia. Liat aja sekarang maraknya gaya-gaya yang dibilang Anto sebagai AMI-like. Karena nongol di kompilasi-kompilasi IAI, nongol di acara "Rumah Idaman" di tivi, dan sebagainya maka asumsi orang bahwa karya arsitektur semacam itulah yang bagus. Jadi ada keterbatasan "perspektif" dari profesional arsitek antara menganut "tren" dari kompilasi itu, dan mengeksplor sendiri karyanya.
Gw ngga men-judge penerbitan buku kompilasi atau coffee-table itu unworthy Nov, tapi perlu juga diimbangin sama terbitnya buku-buku yang eksploratif dan argumentatif. Sama halnya kalo lu bayangin di toko CD kita ngga nemu album musisi favorit kita, dan yang ada kompilasi semua (NOW, 2005 Hits, etc). Darimana kita bisa mengeksplor keindahan nuansa neo-klasik-nya Sarah Brightman, Jamaican-nya Willie Nelson dan sebagainya kalo yang kita nikmatin itu cuman salah satu di antara sekian yang kurang representatif juga.
So, diakhir tulisan gw tentang literatur arsitektur, kesimpulan gw adalah mendorong arsitek-aristek "besar" di Indonesia untuk merilis buku-buku semacam Tibet d'Otak kalo menurut elu, atau Relativitas-nya Adi Purnomo, dan sebagainya untuk mengimbangi rilisan coffee-table yang muncul. Kalo kita lihat, even buku luar yang masuk-pun berupa coffee-table, jadi emang habit kita dipantau sama importir buku sebagai bangsa yang suka mengkopi, bukan berkarya. Gw sendiri, orang yang ngga percaya adanya "gaya" arsitektur setelah munculnya Arsitektur Modern. Arsitektur itu harus pragmatis, dan tidak boleh terikat gaya. Salah satu hal yang melestarikan gaya itu diantaranya adalah keinginan untuk mengkopi.
saya adalah salah seorang yg mengilai buku "AMI perjalanan 1999", yg sangat beruntung sekali saya dapat secara cuma2 dari pak Yori Antar,semasa study eksursi zaman kuliah, dan buku tersebut sampai skrg selalu saya baca sebagai peningkat motivasi saya, saat keraguan untuk bertahan berarsitektur melanda..hmm...dan ttg buku "relativitas"nya Pak Adi Purnomo,saya baru baca review2 dari beberapa blog yg membahasnya..dan sejak membaca reviewnya saja, saya sudah kagum dengan cara berpikir dan berkaryanya pak Mamo..dan buku "relativitas" menjadi most wanted bg saya yg sebenarnya krg bgtu tertarik dalam baca-membaca,terkecuali untuk buku2 hebat seperti "AMI perjalanan 1999" dan "relativitas",tp krna kebetulan di surabaya susah mencarinya..kalau boleh tau dimana ya saya bs mendapatkannya..dan apakah masih ada yg jual saat ini?
Oya, kalau buku "Haikk!" bagaimana?apa ada yg bs mengulasnya?saya juga penasaran dgn isi buku itu...
maaf mas2 semua.. nama saya bagus.. salam kenal ya..saya ingin bertanya..kalau boleh tau dimana ya saya bs mendapatkan bukunya mas adi purnomo? bekasnya juga gk papa kok, pengen baca bukunya mas. maklum baru lulus kuliahnya.
Terimakasih..
Post a Comment